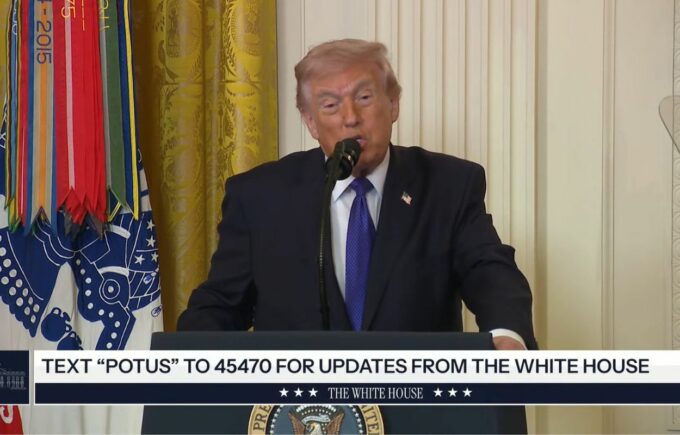Sedang untuk salat duhur dan asar, tidak wajib berjamaah. Maka ketika sore itu dilakukan salat asar, lantai bawah itu tidak penuh. Maka ketika bangunan baru itu roboh, yang enam baris di depan semuanya selamat. Termasuk imam salat, seorang ponakan kiai. Bangunan lama itu tidak terpengaruh sama sekali.
Sampai di mana gerakan salat asar itu ketika bangunan runtuh?
“Sudah rakaat keempat. Sedang posisi sujud. Jenazah yang ditemukan ada yang dalam posisi sujud,” ujar Kiai Abdul Muid.
Salah seorang santri, katanya, merasakan seperti ada gempa kecil sebelum bangunan itu roboh. Mungkin badan pemantau gempa bisa mengecek apakah ada gempa kecil pada jam-jam sebelum itu.
Saya bisa membayangkan alangkah sulitnya tim evakuasi melaksanakan tugasnya hari itu. Bangunan yang roboh itu dijepit bangunan-bangunan lain. Di baratnya ada “bangunan enam baris” yang tidak roboh. Bagian selatannya bangunan-bangunan empat lantai. Timur dan utaranya rumah-rumah tinggal enam bersaudara kiai di situ.
Mungkin perlu ada pemikiran baru: menatap ulang tata bangunan di pondok ini. Membangun kembali memang penting tapi menata ulang tidak kalah penting.
Kiai Asep adalah teladan yang sempurna: pindah lokasi ke kawasan yang cocok untuk pendidikan. Apalagi akses dari jalan raya ke Al Khoziny sangat tidak memadai. Saya harus memutar dulu, lalu jalan kaki menaiki jembatan darurat di atas sungai yang kotor, masih pula harus menyusuri gang yang sempit.
Memang sudah menjadi ciri pondok pesantren untuk menerima keadaan apa adanya. Itu bagian dari ajaran ikhlas. Termasuk menerima musibah besar kemarin sebagai bagian dari takdir. (Dahlan Iskan)