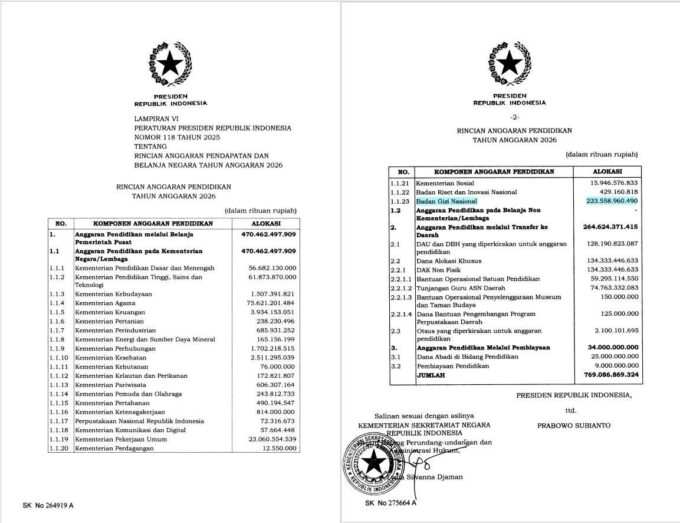2. Lingkungan dan Kesehatan
Dari sisi lingkungan, thrifting bisa punya sisi positif: mengurangi limbah mode (fashion) dengan memperpanjang siklus hidup pakaian, sebagai alternatif terhadap fast fashion.
Tapi, ada juga dampak negatif: beberapa pakaian bekas impor mungkin mengandung bahan berbahaya atau bakteri, karena kualitas dan kebersihan yang tidak selalu terjamin.
Limbah pakaian bekas bisa menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) jika tidak dikelola dengan baik.
3. Regulasi & Legalitas
Ada regulasi di Indonesia yang melarang impor pakaian bekas. Misalnya, Permendag No. 51 Tahun 2015 melarang impor pakaian bekas karena alasan kesehatan dan lingkungan.
Pemerintah melalui instansi seperti DJKN menyoroti bahaya barang ilegal dalam praktik thrifting — tidak semua transaksi thrifting itu legal.
Karena regulasi, ada ketegangan antara pendukung thrifting sebagai gaya hidup berkelanjutan dan pelaku industri tekstil lokal yang merasa dirugikan.
4. Sosial & Budaya
Untuk konsumen, thrifting bisa mendorong gaya hidup lebih bijak (“mindful consumption”). Ada penelitian yang menggunakan model S-O-R (stimulus-organism-response) yang menunjukkan bahwa e-WOM (word-of-mouth di media sosial) bisa mendorong orang membeli pakaian bekas lokal sebagai bagian dari konsumsi berkelanjutan.
Namun, tidak semua orang membeli thrifting karena peduli lingkungan; sebagian karena ingin menghemat uang atau untuk gengsi fashion dengan harga rendah.
Ada kekhawatiran dari desainer dan pelaku industri fashion lokal bahwa keberadaan barang bekas impor bisa mengikis identitas dan inovasi desain lokal.
5. Negara & Keuangan Publik
Karena banyak barang bekas impor dijual secara ilegal, negara berpotensi kehilangan pendapatan bea masuk dan pajak.
Jika tidak diatur dengan baik, arus barang bekas bisa menjadi beban lingkungan dan sosial yang berbiaya pada negara (misal dari sisi pengelolaan limbah).